Indonesia 2050: Menyeimbangkan Ambisi Energi dan Realita

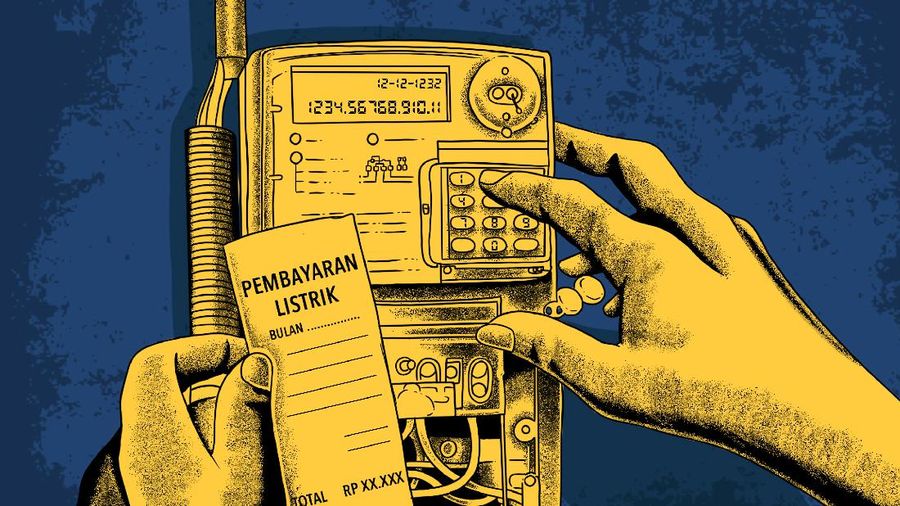
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Tahun 2050 selalu menjadi horizon masa depan penuh harapan dan tantangan sekaligus. Dunia diperkirakan dihuni hampir sepuluh miliar orang, kota-kota membengkak menjadi megapolitan, dan ekonomi global melaju dengan kecepatan tinggi.
Energi akan menjadi urat nadi yang menentukan apakah infrastruktur digital, kendaraan listrik, sektor industri berat, petrokimia, dan kehidupan sehari-hari dapat bertahan atau malah runtuh di bawah beban konsumsi dan tekanan iklim.
Meski energi terbarukan tumbuh pesat di banyak negara, kenyataannya minyak dan gas tetap akan memegang peran penting hingga pertengahan abad ini. Industri berat memerlukan kepadatan energi yang sulit disuplai sepenuhnya oleh surya atau angin; transportasi jarak jauh masih sangat bergantung pada bahan bakar cair; petrokimia tetap menjadi tulang punggung berbagai produk penting.
Oleh karena itu, tantangan utama bukan menghentikan penggunaan fosil secara instan, tapi merancang transisi yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan dan penurunan emisi.
Pada sektor digital, tekanan makin terasa. Pusat data, jaringan 5G dan 6G, kecerdasan buatan, layanan cloud, serta protokol blockchain tak bisa berjalan tanpa pasokan listrik besar dan stabil. Globally, konsumsi energi pusat data sudah setara negara menengah, dan tren ke depan menunjukkan lonjakan eksponensial.
Indonesia, sebagai negara dengan pengguna internet besar dan ambisi menjadi hub digital Asia Tenggara, akan menyaksikan permintaan listrik digital yang tak kalah besar. Bila pusat data kita masih menggunakan listrik dari energi fosil, beban karbon negara ini akan melonjak dan reputasi iklim terancam.
Dalam konteks ini, Indonesia memiliki keunggulan sekaligus beban. Dengan potensi sumber daya yang sangat melimpah, lebih dari 200 GW potensi surya, 75 GW hidro, 29 GW panas bumi, 60 GW angin, 32 GW biomassa, potensi sumber daya ini menunjukkan Indonesia mempunyai pondasi yang langka.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL 2025-2034) menyasar penambahan kapasitas angin 7,2 GW, surya 17,1 GW, hidro 11,7 GW, panas bumi 5,2 GW, dan bioenergi 0,9 GW. Tapi ambisi tanpa dukungan regulasi, investasi, dan jaringan akan tetap menjadi mimpi.
Kemandirian energi tidak cukup hanya membangun pembangkit besar. Ia harus merambah desa, rumah tangga, dan skala mikro. Kisah nyata di salah satu kampung perbatasan Kalimantan Utara menjadi cermin: listrik genset enam jam digantikan dengan kombinasi PLTS, turbin angin dan baterai mini, memberi daya penuh sepanjang malam. Anak-anak bisa belajar tanpa resah listrik padam, usaha kecil tumbuh tanpa hambatan listrik, dan biaya hidup ikut menurun.
Namun, jalur menuju Indonesia merdeka energi penuh liku. Setiap provinsi memiliki potensi berbeda, sebagai contoh potensi angin di NTT dan Sulawesi, air di Kalimantan dan Papua, panas bumi di Sumatra hingga Sulawesi, teknologi laut di Maluku. Peta potensi energi provinsi yang terintegrasi dalam jaringan nasional menjadi kunci agar distribusi pasokan merata.
Hilirisasi juga harus mendapat posisi terdepan. Baterai, panel surya, turbin angin, dan elektroliser hidrogen harus dibuat di dalam negeri. Jangan sampai kita hanya mengekspor bahan mentah. Target yang perlu kita capai adalah agar di tahun 2030 seluruh kebutuhan baterai kendaraan listrik diproduksi domestik dan tahun 2045 Indonesia menjadi eksportir teknologi energi bersih.
Aspek yang tidak kalah penting adalah mengenai cadangan strategis energi. Beberapa negara punya Strategic Petroleum Reserves untuk persediaan 90 hari. Indonesia butuh fasilitas cadangan minyak, LPG bahkan baterai besar sebagai penyangga terhadap gangguan global. Landasan hukum yang disiapkan juga relatif kuat dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 (Cadangan Penyangga Energi) dan kebijakan energi nasional seperti PP No.79/2014 dan UU 30/2007.
Namun, transisi energi yang tidak adil berisiko menimbulkan ketimpangan baru. Masyarakat miskin yang belum memiliki listrik layak masih menggunakan kayu atau arang untuk memasak. Jika kebijakan keputusan hanya menguntungkan kawasan kota, desa akan terpinggirkan. Oleh sebab itu, akses listrik ke pedesaan, subsidi tepat sasaran untuk energi bersih rumah tangga, dan pembangunan infrastruktur di timur Indonesia harus menjadi prioritas.
Di ranah global, energi 2050 akan ditandai bukan oleh volume bahan bakar, melainkan oleh sumber bersih dan kapasitas teknologi. Negara yang menguasai teknologi penyimpanan, jaringan pintar, dan hidrogen hijau akan menjadi pemain utama. Dengan posisi strategis, sumber daya alam kaya, dan letak geografis di jalur perdagangan global, Indonesia berpeluang menjadi pemain besar energi bersih Asia Tenggara.
Proyeksi menunjukkan bahwa konsumsi listrik nasional pada 2050 bisa menembus 1.000 TWh per tahun, dengan kapasitas mencapai 400-430 GW atau lebih dari enam kali kapasitas saat ini. Konsumsi listrik per kapita Indonesia berpotensi bisa mencapai sekitar 7.000 kWh. Di masa itu, kita harus punya jaringan andal, pembangkit fleksibel (gas, hydro reservoir), penyimpanan besar dan sistem manajemen beban yang cerdas.
Akhirnya, 2050 bukan sekadar soal angka megawatt atau terawatt jam. Itu adalah soal kualitas hidup yang bisa dinikmati rakyat seperti udara bersih, iklim yang stabil, munculnya pekerjaan hijau, dan masa depan digital yang tidak membebani bumi. Keputusan hari ini, memilih antara memperpanjang masa PLTU atau mempercepat ladang surya, memberi subsidi bahan bakar atau menyokong inovasi energi, dapat menjadi warisan terbesar kita bagi generasi mendatang.
(miq/miq) Add
 as a preferred
as a preferred
source on Google