Sejarah Migas: Ada Warisan Petani Jawa di Kontrak Migas RI
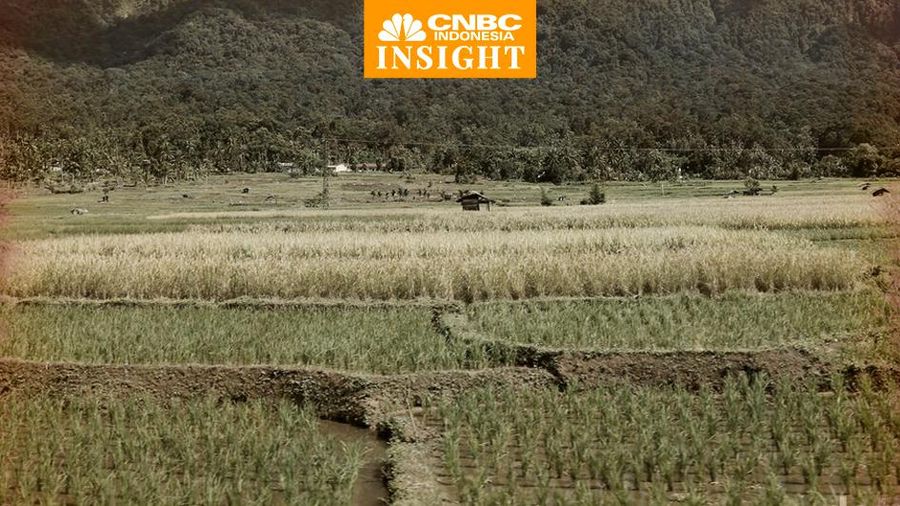
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Soekarno terinspirasi dari petani-petani di Jawa dalam mengeluarkan Kontrak Bagi Hasil minyak dan gas (migas) bagi investor. Kok bisa?
Saat ini, Indonesia kini telah menjadi net importir minyak, namun tak dapat dipungkiri bahwa industri hulu minyak bumi dan gas (migas) masih menjadi andalan untuk mendongkrak perekonomian bangsa. Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saja, industri hulu migas RI telah menyumbang ratusan triliun rupiah per tahunnya.
Bahkan, berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), pada 2022 lalu Indonesia meraup US$ 18,19 miliar atau sekitar Rp 275,6 triliun (asumsi kurs Rp 15.154 per US$) dari sektor hulu migas nasional.
Untuk mempertahankan dan bahkan menggenjot produksi migas nasional dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara, maka dibutuhkan investasi, bukan hanya dari pihak dalam negeri namun juga dari asing. Adapun bentuk pengikat kerja sama dengan investor migas ini biasa dikenal dengan Kontrak Bagi Hasil atau Kontrak Kerja Sama (KKS) atau Production Sharing Contract (PSC).
Kontrak Bagi Hasil ini biasanya ditandatangani antara badan pengelola hulu migas, dalam hal ini SKK Migas, dengan investor atau kontraktor migas atau biasa disebut Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Kontrak ini ditandatangani setelah pemerintah menetapkan pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) atau blok migas dan kedua belah pihak telah menyepakati syarat dan ketentuan (term & conditions).
Setelah ditandatanganinya PSC ini, maka investor akan melanjutkan kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan dan bila akhirnya menemukan cadangan ekonomis untuk dikembangkan skala besar, maka kontraktor pun akan melanjutkan pada tahapan eksploitasi atau produksi.
Adapun ketika produsen atau kontraktor telah berhasil menjual minyak dan gasnya, maka pendapatan ini akan dibagi dua yakni untuk pemerintah pusat sebagai "penguasa tanah" dan kontraktor sebagai "pekerja". Biasanya, selama ini bagi hasil minyak yakni 85% untuk pemerintah dan 15% untuk kontraktor. Sementara untuk gas biasanya 70% untuk pemerintah dan 30% untuk kontraktor. Namun, pemerintah akan mengembalikan biaya kepada kontraktor dalam bentuk Cost Recovery, sehingga skema kontrak migas disebut dengan Kontrak Migas Cost Recovery.
Namun, siapa sangka kalau perhitungan yang rumit dan sering mengundang kontroversi karena dianggap tak adil ini berawal dari perhitungan sederhana para petani masa kuno.
Hal ini diungkap oleh Widjajono Partowidagdo dalam buku Migas dan Energi di Indonesia: Permasalahan dan Kebijakan (2009). Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2011-2012 ini, sistem bagi hasil migas ini diprakarsai oleh Presiden Soekarno ketika melihat model bagi hasil pertanian di Jawa.
Sawah-sawah yang terhampar luas di pedesaan kebanyakan tidak dimiliki langsung oleh para petani. Mereka hanya menggarap lahan pemilik sawah. Agar mencapai asas keadilan, terjalinlah bentuk perjanjian antara keduanya. Bahwa jika penggarap berhasil mengolah sawah, maka dia berhak mendapat pembagian hasil yang telah disetujui bersama oleh pemilik lahan. Misal, petani dapat 40% dan pemilik 60%.
Hitung mundur ke ribuan tahun silam, sistem seperti ini memang menjadi kelaziman di masyarakat pertanian masa lalu atau tepatnya ketika feodalisme masih mengakar kuat di Jawa. Menurut Ong Hok Ham dalam Wahyu yang Hilang Negeri Yang Guncang (2019), para petani biasanya menganut sistem subsisten. Artinya, dia bertani di tanah sendiri, lalu hasilnya sekedar cukup untuk dikonsumsi sendiri. Jika ada hasil lebih, maka akan diberi ke orang lain secara sukarela atau dijual.
Namun, sistem ini perlahan berubah muncul feodalisme atau ketika kerajaan-kerajaan Hindu Budha bermunculan di Nusantara. Feodalisme berasal dari kata feodum yang berarti tanah. Pada sistem ini, tanah dan bangunan menjadi milik bangsawan atau raja. Sedangkan, rakyat diminta untuk bekerja kepada penguasa berdasarkan arahan tertentu.
Mengutip Subroto dalam Sistem Pertanian Tradisional Pada Masyarakat Jawa Tinjauan Secara Arkeologis dan Etnografis (1985), raja sebagai penguasa tertinggi dalam suatu kerajaan mempunyai hak untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, termasuk mengambil alih kepemilikan lahan pertanian. Semua itu dimaksudkan untuk memenuhi fungsi pokok seorang raja sebagai pelindung seluruh rakyatnya.
Diambilnya sawah oleh raja membuat pemilik lahan berubah menjadi penggarap. Mereka melakukan penggarapan atas perintah raja. Hasilnya diberikan sebagai upeti. Namun, agar tidak terkesan memperbudak penduduk, lahirlah sistem bagi hasil bumi. Penggarap tanah juga tetap mendapat keuntungan meskipun tidak sebesar raja.
Meski era kerajaan sudah berakhir, sistem ini justru terus bertahan. Di masa kolonial juga terjadi sistem bagi hasil pertanian antara bangsawan dengan pribumi. Bahkan, pemerintah kolonial pada 1903 tercatat pernah mengatur hal ini dalam skala ekonomi makro.
Hingga kini, sistem bagi hasil pertanian ala petani kuno diadopsi oleh negara modern bernama Indonesia.
(mfa/mfa)[Gambas:Video CNBC]